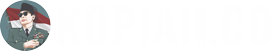Kopiah.co – Pergulatan ideologi negara dengan mayoritas umat muslim—yang menjadi negara jajahan—pasca kolonialisme menjadi pembahasan menarik yang memotret dialektika pembaharuan pemikiran Islam dalam ranah politik.
Kesadaran umat Islam akan keterbelakangan membuahkan wacana-wacana baru dalam membangun sebuah negara, Islam menjadi sebuah spirit dan sekaligus menjadi identitas dalam membangun peradaban baru setelah dibuat babak belur oleh kolonialisme.
Garis permulaan perbincangan ini adalah invasi Napoleon Bonaparte ke Mesir pada abad kesembilan belas yang menandai awal dari kolonialisme dan jatuhnya imperium agung Utsmaniyyah setelah berkuasa selama 624 tahun lamanya menggemparkan umat muslim di seluruh penjuru dunia. Otoritas kenegaraan terbesar yang telah meninabobokan peradaban Islam selama berabad-abad kini sudah tidak bisa menjadi harapan umat Islam.
Di sisi lain, mereka ternyata sadar bahwa pada fase ini, umat Islam tengah berada dalam kolonialisme yang mengisap segala sumber daya yang dimiliki negara-negara atau kerajaan Islam. Pertanyaan besar yang dilahirkan dari realitas ini adalah imajinasi politik seperti apa yang dicita-citakan umat Islam dalam membangun kembali kekuatan politik setelah diporak porandakan oleh imperialisme dan kolonialisme? Kesadaran inilah yang selanjutnya mengantarkan politik umat Islam—sebagai mayoritas bangsa jajahan—menuju arah yang bercorak revolusioner yang bermacam-macam.
Aliran-Aliran Pembaharuan Pemikiran Politik Islam
Akar kesadaran inilah yang di kemudian hari menyuburkan pembaharuan pemikiran politik umat muslim. Menurut Fazlur Rahman dalam bukunya yang berjudul “Islam”, Jamaluddin Al Afghani adalah tokoh sentral dalam pergulatan pembaharuan pemikiran politik umat muslim yang ia tuangkan dalam majalah al-urwah al-wusqa yang ia gagas bersama Muhammad Abduh di Paris, wacana kebangkitan umat Islam dalam bidang politiknya menekankan persatuan umat Islam dan juga populisme yang berfokus pada kepentingan rakyat, meskipun wacana pembaharuan politik yang digaungkan Afghani tidak terlalu berdampak signifikan dalam aktualisasi politik umat Islam, namun mempengaruhi pemikiran-pemikiran politik setelahnya.
Pada fase berikutnya, wacana Afghani ini direspon dengan sudut pandang yang beragam oleh kalangan cendekiawan muslim abad dua puluh, setidaknya pandangan Afghani melahirkan dua spektrum politik yang saling bertolak belakang, islamisme revivalis yang mencita-citakan persatuan umat Islam di bawah naungan otoritas pemerintahan tunggal dan Nasionalisme.
Kelompok pertama mengimajinasikan adanya negara agama yang berfungsi sebagai pijakan bagi penegakan hukum-hukum Islam dalam sebuah komunitas, kemudian merawat serta mengembangkan umat dengan cara-cara Islami, berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dengan begitu maka Islam tidak hanya berisi dimensi esensial nilai-nilai agama, namun juga harus diinstitusionalisasikan dalam bentuk negara untuk menerapkan hukum-hukumnya, lebih lanjut dengan pemaknaan yang lebih radikal, Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa Islam adalah peribadatan dan pemerintahan, agama dan negara, spiritual dan pengamalan, shalat dan jihad, Al-Quran dan pedang, kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Terakhir, mereka melihat Islam sebagai identitas politik global yang harus melampaui batas-batas negara.
Wacana islamisme revivalis ini diorganisir lewat partai politik maupun kelompok-kelompok yang berasaskan keagamaan, di Mesir wacana ini disuburkan oleh Ikhwanul Muslimin yang dibentuk di kota Ismailia, Mesir pada Maret 1928 oleh Hasan Al Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin tersohor lainnya adalah Sayyid Qutb dan Abdul Qadir Audah, IM pada awalnya merupakan sebuah organisasi dakwah yang pada kemudian hari aktif dalam politik Mesir. Di Pakistan, wacana revivalisme ini dibawa oleh Abul A’la Al Maududi lewat Jamaah Al-Islamiyyah yang didirikan pada 26 Agustus 1941 di Lahore, India—sebelum menjadi bagian dari Pakistan—, kelompok ini pada fase selanjutnya menyebar ke berbagai negara seperti Lebanon, Suriah, bahkan Indonesia.
Kelompok kedua, adalah mereka yang berada pada barisan nasionalisme yang cenderung melihat umat sebagai sebuah komunitas yang harus mengedepankan identitas nasional dan negara-bangsa, serta berakar pada nilai-nilai budaya, bahasa dan tradisi lokal, dalam bentuk ekstrem, kelompok ini cenderung menggunakan cara pandang sekuler yang bertolak belakang dengan kaum islamisme revivalis
Kelompok nasionalis sekuler menganggap bahwa Khilafah yang digaungkan oleh kelompok Islamis bukanlah sistem yang bersumber dari syariat Islam, melainkan sistem yang bersumber dari sejarah peradaban Islam yang—pernah—digunakan dalam periode tertentu. Menurut Ali Abdul Raziq dalam bukunya Al-Islam wa Ushul al-Hukm, bahwa tidak ada dalil eksplisit dari Al-Qur’an maupun Hadits yang menunjukkan kewajiban mendirikan khilafah. Penegasan ini penting karena Al-Qur’an dan Hadits nabi merupakan sumber utama hukum Islam, adapun penentuan penobatan khilafah atau imamah dalam sejarah Islam hanyalah hasil Ijtihad para ulama yang hidup dalam konteks mereka—yang—meskipun sahih dalam tradisi hukum Islam, menunjukkan kelemahan dalam memberikan legitimasi teologis yang kuat terhadap doktrin keharusan menggunakan sistem khilafah.
Turki di bawah Mustafa Kemal Ataturk adalah implementasi sekularisme paling sempurna dalam hal ini yang menjadi pandangan kedua dalam pembaharuan politik umat Islam, Islam diartikan sebagai aspek keyakinan dan peribadatan individu dan tidak berkutat pada tatanan sosial masyarakat dalam negara.
Prinsip Bernegara Dalam Islam
Sistem politik bagi umat Islam bukanlah suatu esensi dari agama itu, bukan syariat, dan bukan suatu keharusan bagi manusia muslim, menurut Abdul Raziq, sistem politik seyogyanya dikembalikan kepada masing-masing komunitas berdasarkan historisitas politik, budaya setempat, kesepakatan warga negara, dan hal-hal lainnya yang menunjang kemajuan suatu bangsa
Prinsip-prinsip dalam bernegara menurut Islam lebih rinci dijabarkan oleh Muhammad Thahir bin ‘Asyur dalam bukunya Ushul al-Nidzam al-Ijtima’i fi al-Islam, pertama-tama ibnu ‘Asyur mengklasifikasikan prinsip ini kepada dua cabang, prinsip interaksi antar warga negara, dan prinsip kebijakan politik.
Pertama, interaksi sosial antar warga negara, prinsip ini bertujuan mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat agar tercipta masyarakat yang harmonis, titik berat prinsip ini ialah pembentukan moral dan solidaritas sosial yang bergantung pada tingkat kecerdasan beragama dan moral individu. Pada bagian ini Islam mengajarkan kepada manusia nilai-nilai budi pekerti yang luhur, keadilan, kesetaraan, persatuan, gotong-royong, saling mencintai, dan kemurahan hati.
Kedua, prinsip kebijakan politik, yang berorientasi pada pengelolaan masyarakat secara kolektif demi mencapai tujuan syariat (maqashid syariah). Di sini, Islam mengajarkan aspek keadilan sosial, pengelolaan ekonomi, perlindungan wilayah, kesetaraan, kebebasan, penetapan hak, keadilan, menjaga harta kekayaan umat, memakmurkan sumber daya, serta melindungi otoritas wilayah, sehingga dengan begitu suatu negara dapat merawat umat dengan sempurna, dan menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Prinsip-prinsip ini menggambarkan syariat Islam yang holistik dalam menciptakan bangsa yang kuat secara ketatanegararaan dan masyarakatnya yang hidup secara harmonis, Ibnu ‘Asyur menekankan keseimbangan antara moralitas individu dan kekuatan institusional. Ia menawarkan model tatanan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kebijakan praktis politik.
Pengalaman Kebangsaan Indonesia
Dalam konteks negara kita, bangsa Indonesia melakukan penggalian jati diri politiknya dengan sempurna, historisitas Indonesia dan kekayaan budaya digunakan para pendiri bangsa untuk menciptakan asas politik bangsa yang paripurna, buahnya, dalam tatanan implementatif seluruh aspek dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam dibubuhkan dalam keindonesiaan kita, hal ini tercermin dengan nyata dalam lima sila yang menjadi falsafah bangsa ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sukarno, bahwa pancasila ini merupakan hasil penggalian mendalam atas kekayaan yang terkandung dalam buminya Indonesia.
Indonesia secara konstitusi bukanlah negara agama yang menjadikan teks agama sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan kenegaraan, keragaman agama yang diberikan Allah pada bumi Indonesia ini mendorongnya untuk menemukan titik bersama, kalimatun sawa nya Indonesia dalam merumuskan asas-asas kenegaraan. Indonesia juga bukan negara nasionalis bercorak sekuler yang menegasikan agama dari cara pandang berbangsa dan bernegara.
Realitas Indonesia adalah kombinasi sempurna dari ide nasionalisme moderat dan islamisme esensial yang mampu memeras nilai-nilai keislaman dengan sempurna dan selanjutnya diintegrasikan dengan wacana nasionalisme, belum lagi sinkretisme agama dengan kebudayaan lokal yang berjalan dengan mulus menisbatkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan beragama.
Dari sini kita bisa memotret bahwa abad kesembilan belas merupakan lonceng penyadaran umat Islam, setelah kekaisaran Utsmaniyyah runtuh dan Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir, umat tersadarkan akan kelemahan politik mereka, inilah yang memacu cendekiawan muslim untuk memikirkan ulang politik umat lewah berbagai wacana pembaharuan pemikiran politik, baik yang mencita-citakan terbentuknya kembali persatuan umat Islam dalam satu bendera dan batas negara maupun yang mencita-citakan suatu negara bangsa yang terbentuk berdasarkan kontrak sosial suatu wilayah di luar aspek agama, menjadikan rasionalitas historis masyarakat sebagai rujukan utama pembangunan negara bangsa. Indonesia—yang juga negara dengan umat muslim terbesar—mempunyai sikap moderat dalam menyikapi dua spektrum yang berseberangan ini, mengambil nilai-nilai keislaman untuk selanjutnya diintegrasikan dalam nasionalisme negara bangsa modern.