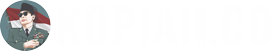Ibu kita Kartini
Putri sejati
Putri Indonesia
Harum Namanya
Semenjak duduk di bangku TK, saya sudah dikenalkan dengan seorang tokoh yang namanya diabadikan Wage Rudolf Supratman dalam bait-bait lagu di atas, Raden Ajeng Kartini. Lagu tersebut saya nyanyikan di kelas setiap Senin pagi bersama kawan-kawan dengan suara lantang. Karena masih kecil, saya tidak punya pertanyaan-pertanyaan seputar sosok yang disebut sebagai “Ibu Kita”: kenapa ia adalah putri sejati dan harum namanya. Ketakacuhan tersebut terjadi seperti angin lalu sampai saya bertemu dengan terjemahan buku yang ditulis perempuan tersebut, Habis Gelap Terbitlah Terang. Saya menyadari betul betapa perempuan bernama Kartini itu memiliki perjuangan dan gagasan-gagasan yang luar biasa tentang berbagai hal, terutama tentang emansipasi wanita, karena buku tersebut.
Terlahir dalam lingkungan bangsawan pada 21 April 1879 tidak serta-merta membuat Kartini hidup dalam kebahagiaan. Diangkatnya sang ayah, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, menjadi bupati Jepara pada masa itu justru membawa kegetiran tersendiri dalam hidup Kartini. Mula-mula, sesuai dengan peraturan Belanda yang mengharuskan bupati menikah dengan keturunan raja, Kartini harus memanggil ibu kandungnya sendiri (Nyai Ngasirah) dengan panggilan Yu atau Mbakyu (sebutan yang biasanya digunakan untuk memanggil pembantu) dan hanya boleh memanggil Ibu kepada ibu tirinya saja yang memiliki garis keturunan kerajaan Madura, Raden Ayu Moeryam. Selanjutnya, ia harus mengelus dada ketika melihat ibu kandungnya sendiri harus berjalan menunduk di hadapannya karena mengikuti adat kebangsawanan Jawa kala itu.
Budaya kebangsawanan tidak hanya menyakiti Kartini sampai di situ saja. Ia turut serta mengubur cita-cita Kartini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada masa itu, Kartini hanya diperbolehkan menamatkan pendidikan sampai jenjang setara sekolah dasar di ELS (Europese Lagere School). Selanjutnya, ia harus menjalani masa pingitan, sebuah masa di mana perempuan harus menjalani kurungan dalam rumah sampai ada lelaki yang melamarnya. Semua hal tersebut praktis membuat Kartini berpikir bahwa perempuan di masanya tidak mendapatkan keadilan serta kesetaraan hak dengan laki-laki dalam banyak hal.
Perempuan yang usianya belum sampai seperempat abad itu akhirnya sadar bahwa dirinya harus melawan hukum-hukum yang dianggapnya konyol. Beruntungnya, kakaknya, Sosrokartono, memiliki pemikiran yang sama dengan Kartini: semua orang pada dasarnya berhak mendapatkan hak yang sama. Walhasil, meski berada dalam pingitan Kartini tetap bisa mengakses ilmu pengetahuan seluas-luasnya melalui buku-buku yang diberikan oleh kakaknya. Kartini melawan maka ia membaca.
Selain mendapat dukungan dari kakaknya, Kartini juga belajar banyak dari seorang Belanda teman ayahnya yang bernama Nyonya Ovink Soer. Diawali dari koneksinya dengan Ovink Soer, Kartini mulai berkorespondensi dengan beberapa penulis Belanda yang lain—antara lain Stella Zeehandelaar dan JH Abendanon—untuk bertukar pikiran tentang berbagai hal, terutama feminisme. Melalui surat yang ditulisnya Kartini bercerita bahwa perempuan-perempuan di Jawa tidak memiliki hak yang setara dengan pria sebagaimana yang ada di Belanda. Ia juga menuangkan opininya soal bagaimana seharusnya perempuan diperlakukan. Bila boleh saya simpulkan, secara garis besar terdapat tiga ide gagasan penting feminisme Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan.
Pertama, mendirikan sekolah khusus perempuan. Perempuan bagi Kartini adalah sosok yang seharusnya mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, karena kelak, ia adalah orang yang pertama kali mendidik tunas-tunas bangsa. Perempuan harus terdidik sebelum mengemban tugas mendidik. Namun realitasnya, perempuan masa itu hanya boleh memiliki satu cita-cita: menikah. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain menikah. Pasalnya, pada masa itu perempuan yang tak kunjung menikah dianggap aib besar.
Pada dasarnya, Kartini tidak memungkiri bahwa nikah adalah suruhan Tuhan. Yang menjadi problem baginya adalah pernikahan yang dijalani perempuan zamannya bukan murni keinginan mereka sendiri, melainkan karena perintah bapaknya yang telah melakukan perjanjian dengan seseorang yang sama sekali asing baginya. Nahasnya, karena tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan untuk menghindari pernikahan yang tidak diinginkannya, perempuan-perempuan itu hanya bisa pasrah dengan hati yang tersakiti.
Bagi Kartini, adat seperti itu harus dia lawan. Perempuan Jawa harus memiliki kebebasan atas hidupnya sendiri. Cita-cita seperti itu, menurut Kartini, hanya bisa dicapai ketika para perempuan mendapatkan pendidikan layak sehingga ia dapat memahami kehidupan sepeti apa yang patut dijalaninya dan diperlakukan berdasarkan kemanusiaan. Dalam suratnya kepada Nyonya Van Kol (Agustus 1901) Kartini bahkan memohon agar perempuan Jawa mendapatkan pendidikan: “Ajarilah dia sesuatu, supaya janganlah lagi jadi kurban.”
Kedua, memberikan kebebasan kepada perempuan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pemikiran Kartini terkait kebebasan memilih pekerjaan bagi perempuan cukup sederhana. Menurutnya, Allah telah memberikan manusia talenta sesuai dengan yang dikehendakinya. Oleh karena itu, manusia, baik laki-laki atau perempuan, sudah seharusnya bebas memilih pekerjaan apa saja untuk dirinya sejauh memberikan manfaat.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Nyonya Ovink-Soer (1900) Kartini sendiri menyebutkan cita-cita pekerjaan yang bakal ia jalani bersama kedua adiknya. Ia dan Kardinah akan menjadi guru agar dapat memberikan bimbingan serta pengetahuan kepada para gadis bumiputera. Sementara Rukmini akan bekerja dalam bidang kesenian supaya dapat menghidupkan kembali seni di Hindia kala itu. Jika kebebasan memilih pekerjaan berhasil diterapkan, dampak positifnya, menurut Kartini, tidak hanya mengarah kepada kaum perempuan saja. Pekerjaan kaum laki-laki sedikit banyak juga terbantu oleh perempuan yang memiliki talenta di bidang yang sama.
Ketiga, menghapus adanya poligami. Adalah sesuatu yang aneh menurut Kartini ketika hukum Islam mengizinkan laki-laki untuk menikahi empat orang perempuan. Parahnya lagi, itu bukan dosa menurut hukum Islam, bahkan menurut sebagian ulama hukumnya sunah. Namun Kartini memiliki pandangan yang berbeda, poligami baginya adalah dosa. “Segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya dosalah pada mataku,” ujar Kartini. Selanjutnya, Kartini memberikan gambaran betapa poligami memberikan rasa sakit yang amat bagi perempuan: “Betapakah azab sengsara yang harus diderita seorang perempuan, bila lakinya pulang ke rumah membawa perempuan lain, dan perempuan itu harus diakuinya perempuan lakinya yang sah, harus diterimanya jadi saingannya?”
Latar zaman dimana Kartini hidup memang memperlihatkan fenomena lumrahnya poligami. Bahkan, ayahnya sendiri juga berpoligami agar dapat menduduki jabatan sebagai bupati Jepara. Namun, keadaan tersebut tidak bukan berarti membuat Kartini bungkam atas budaya yang tidak disukainya. Ia menentang keras adanya poligami. Hampir di semua surat-suratnya Kartini menyebut poligami sebagai budaya yang harus dibasmi.
Yang menarik bagi saya adalah, untuk menguatkan opininya, Kartini mengutip sebuah hadis yang menceritakan percakapan Rasul saw. dengan Fatimah. Rasul menanyakan kepada Fatimah bagaimana jika Ali menikah lagi. Fatimah menjawab, tidak masalah. Namun ketika ia bersandar pada pohon pisang, semua daunnya yang mulanya segar dan subur menjadi layu dan batangnya menjadi hangus. Pertanyaan yang sama dilontarkan lagi oleh Rasul dan dijawab sekali lagi oleh Fatimah dengan jawaban yang sama. Kali ini, Rasul memintanya meletakkan telur mentah di dadanya. Kemudian Nabi memintanya kembali, mengupasnya, dan ternyata telur itu telah masak. Cerita Fatimah tersebut, menurut Kartini, menjelaskan kepada kita betapa pikiran kebanyakan perempuan menganggap kejam praktek poligami.
Setiap ide dan gagasan dalam sebuah perjuangan tidak mesti mendapati jalan yang manis. Dalam memperjuangkan gagasan-gagasannya terkait hak-hak perempuan Kartini mendapati banyak batu sandungan. Rencana studinya ke Belanda mendapati kegagalan, ia juga harus menikah dengan seorang bupati Rembang (Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat) yang sudah pernah menikah tiga kali. Namun gagasan-gagasannya terus ia pertahankan hingga akhirnya tokoh emansipasi wanita itu menemui ajalnya pada tanggal 17 September 1904 beberapa hari usai melahirkan anak pertamanya. Usianya di waktu meninggal masih relatif cukup muda, yakni 25 tahun. Kartini memang sudah meninggal, tetapi gagasan-gagasannya terus hidup hingga sekarang.
Selamat memperingati hari kelahiran Kartini!